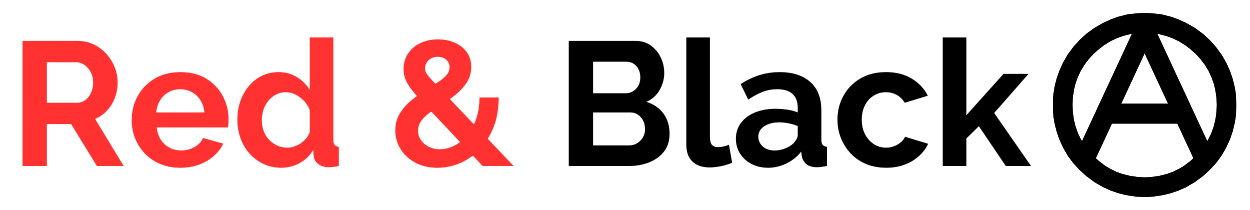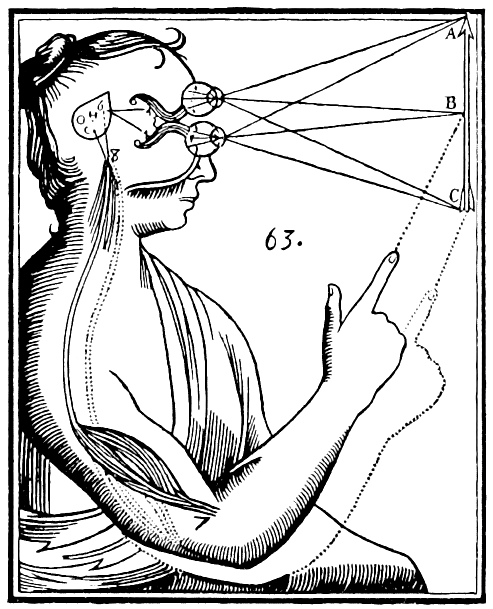Bagaimana Keterwakilan-isme Membunuh Perlawanan Rakyat:
Refleksi atas Gelombang Demonstrasi Agustus - September di Indonesia
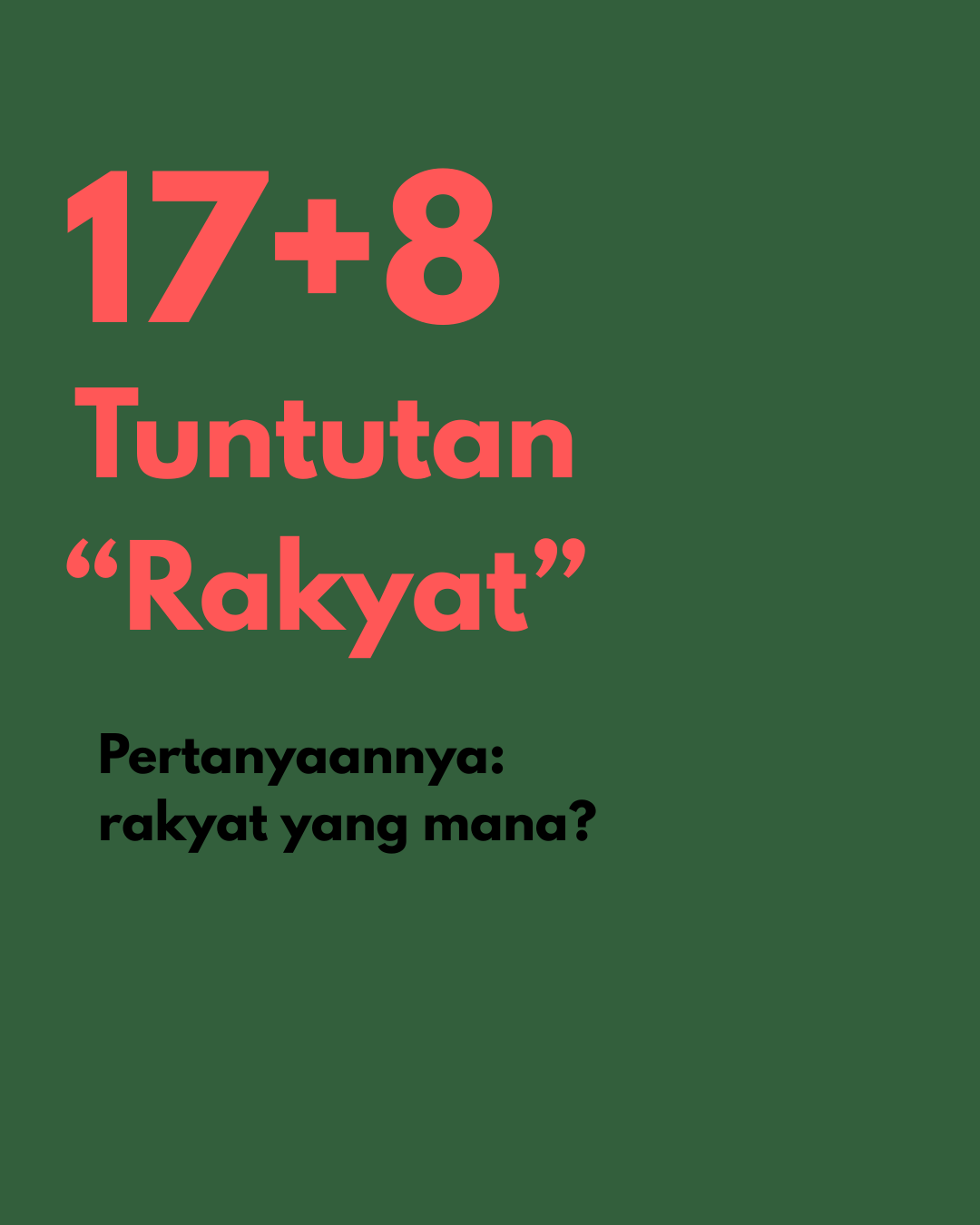
Untuk diingat: Tulisan ini adalah refleksi pribadi dan tidak dimaksudkan untuk mewakili pandangan orang lain atau kelompok tertentu.
Satu dua bulan terakhir, gelombang perlawanan rakyat terjadi di berbagai belahan dunia. Terbaru, gelombang demonstrasi besar-besaran di Madagaskar terjadi dan berhasil membuat goncangan politik yang besar. Kemarahan ini merupakan akumulasi dari penderitaan yang telah dialami oleh rakyat Madagaskar selama bertahun-tahun, di mana Madagaskar merupakan salah satu negara termiskin di Afrika, membuat 75% penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Buruknya layanan listrik dan air yang hanya dinikmati oleh 36% warganya memperparah kondisi ekonomi yang sudah ada, menjadi pemicu meledaknya kemarahan rakyat pada 25 September 2025. Per awal Oktober 2025, Komisaris Tinggi HAM PBB mencatat setidaknya 22 orang meninggal dan ratusan mengalami luka-luka dalam rangkaian demonstrasi ini. Kemarahan rakyat yang bertransformasi menjadi perlawanan rakyat –dan sayangnya harus menelan korban jiwa itu– pada akhirnya berhasil membuat pemerintahan Madagaskar dibubarkan.
Kurang lebih 3 minggu sebelumnya, Nepal juga mengalami hal serupa. Dipicu oleh tingginya jurang kemiskinan antara rakyat biasa dan pejabat serta anak-anaknya yang biasanya umum kita sebut dengan istilah nepo babies, serta pengerukan sumber daya alam lewat praktik tambang yang merusak alam oleh para oligarki, kemarahan rakyat meledak pada 08 September 2025 yang dalam waktu 48 jam mampu menggulingkan pemerintahan Nepal. Guncangan politik itu, sayangnya, disertai dengan harga yang kelewat mahal: sebanyak 72 orang meninggal dalam kerusuhan ini, dibunuh aparat negara.
Kita tentu bisa berdebat apakah goncangan politik ataupun perubahan lanskap politik yang dihasilkan dua gelombang perlawanan rakyat di atas membawa hasil yang ideal atau tidak. Tapi, toh, orang-orang Nepal dan Madagaskar menganggapnya sebagai kemenangan. Yang mengejutkan, dua gelombang perlawanan rakyat di atas disebut terinspirasi dari gelombang perlawanan rakyat di Indonesia yang terjadi pada akhir Agustus hingga awal September 2025. Seperti yang terjadi di Nepal dan Madagaskar, gelombang demonstrasi di Indonesia juga memakan korban jiwa. Namun, berbeda dengan dua gelombang kemarahan rakyat lainnya, yang terjadi di Indonesia justru sebaliknya: gerakan ini kemudian mati terlalu dini.
Faktanya, tak hanya 10 orang meninggal, ratusan lainnya masih ditangkap dan perburuan terhadap para demonstran lainnya masih berlangsung hingga saat ini. Sebuah harga yang kepalang mahal untuk sebuah ironi: gelombang perlawanan rakyat di Indonesia berhasil menginspirasi rakyat Nepal dan Madagaskar merebut apa-apa saja yang mereka maknai sebagai kemenangan, namun gagal di negaranya sendiri.
Perlawanan Rakyat Indonesia, Agustus - September 2025
Semua hal yang menjadi alasan kemarahan rakyat di Nepal dan Madagaskar terjadi di Indonesia: nepo babies menduduki jabatan-jabatan publik, jurang kemiskinan antara rakyat biasa dengan pejabat politik dan para oligarki, pengerukan dan eksploitasi sumber daya alam yang hasilnya hanya dinikmati sekelompok orang, korupsi, dan buruknya pelayanan publik adalah sebagian dari banyak hal serupa lainnya yang dapat kita lihat sebagai benang merah dari situasi yang terjadi di Nepal, Madagaskar, dan Indonesia.
Faktanya, jurang kemiskinan yang kelewat tinggi antara orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan yang diperhadapkan dengan anggota-anggota DPR yang digaji kelewat tinggi, serta pernyataan dan penampilan publik mereka yang kerap memamerkan kekayaan disertai komentar-komentar yang merendahkan rakyat, membuat ribuan orang turun ke jalan pada 25 September 2025. Bila mau melihat sedikit lebih jauh, hal hampir serupa terjadi di Pati dua minggu sebelumnya, ketika ribuan warga Pati meluapkan kemarahan mereka di ruas-ruas jalan terhadap pemerintah lokal mereka menyikapi naiknya pajak hingga ratusan persen.
Sejak 25 September 2025, gelombang perlawanan rakyat terus berlangsung dan kemarahan mereka semakin tak terbendung tatkala 3 hari setelahnya, polisi membunuh seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan dalam demonstrasi lanjutan di Jakarta. Brutalitas polisi bukan hal baru dalam sejarah represifitas polisi dalam menangani demonstrasi, namun Affan Kurniawan yang mati dilindas barakuda Brimob, merujuk pada the last straw phenomenon, menjelma sedotan terakhir yang membuat menara sedotan itu jatuh berantakan.
Sejurus kemudian, ribuan orang tergabung dalam gerakan tanpa pemimpin di seluruh penjuru Indonesia. Di ruas-ruas jalan, orang-orang terlibat dalam perkelahian melawan polisi. Tanpa dipimpin oleh siapapun, orang-orang bahu-membahu dalam kerjasama yang setara menciptakan sebuah sistem perlawanan bernafas panjang.
Di sebuah jembatan di Jakarta Timur, misalnya, orang-orang mencopot tongkat-tongkat bambu dan melemparkannya ke ruas jalan di bawahnya sebagai suplai senjata bagi orang-orang yang “berperang” di sana. Di titik-titik lain, orang-orang melempari dan membakar kantor-kantor polisi, yang tentu saja dibalas dengan gas air mata yang tak terhitung jumlahnya. Ketika orang-orang ini lelah, maka akan ada orang-orang lain yang maju untuk memberikan kesempatan mereka untuk mundur dan beristirahat untuk mengisi ulang energi mereka. Siklus ini sukses memperpanjang stamina, sebab di beberapa titik, perlawanan terjadi hampir tanpa henti selama berhari-hari.
Gelombang perlawanan ini juga diikuti oleh begitu banyak orang yang sebelumnya apolitis. Banyak dari mereka turun ke jalan tanpa persiapan, dan mungkin tanpa pengetahuan soal apa yang harus dilakukan. Namun demikian, mereka tetap mendapatkan semua kebutuhan yang mereka perlukan dalam menghadapi gas air mata ataupun surveilans Negara, karena tak kalah banyak orang-orang yang membagi-bagikan apa yang diperlukan.
Pada saat itu, orang-orang yang tidak memiliki kesempatan untuk turun ke jalan tidak mau kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi. Selain turut menyuarakan kemarahan mereka di media sosial, banyak yang juga menyumbangkan uangnya untuk memenuhi kebutuhan logistik para demonstran. Itulah sebabnya orang-orang bergotong-royong menyediakan suplai logistik seperti makanan dan air bagi para pendemo, juga pasta gigi ataupun hal-hal lain yang dipercaya mampu mengurangi efek gas air mata, serta masker penutup wajah untuk menghindari identifikasi identitas mereka.
Semua saling bahu-membahu. Orang-orang yang turun ke jalan tidak merasa lebih baik daripada yang bersuara di media sosial atau menyumbang uang, begitu pun sebaliknya. Semua setara dalam gotong-royong menyuarakan kemarahan organik mereka.
Rupanya, jurang kemiskinan serta kekerasan berulang polisi yang mengerucut pada kematian Affan Kurniawan menjelma perang terbuka yang terjadi di banyak daerah. Kantor-kantor polisi di berbagai tempat dilempari batu, dibakar,menjadi sasaran kemarahan rakyat atas brutalitas sistemik yang selalu dilakukan institusi tersebut.
Penjarahan rumah anggota-anggota DPR dan menteri terasa dilakukan dalam semangat redistribusi kekayaan. Perusakan gedung parlemen di berbagai kota seperti tampil sebagai perwujudan orang-orang yang mulai tidak percaya pada politik perwakilan. Rakyat seolah saling bersepakat bahwa kemarahan ini harus bersifat vertikal, dan bahwa polisi, kekuasaan eksekutif, serta anggota DPR adalah bagian dari sistem penindasan yang sama.
17 + 8: Kegagalan Gagasan Keterwakilan-isme
Lalu tiba-tiba, sekelompok influencer di Indonesia berinisiatif membuat sebuah gerakan yang kemudian kita sebut sebagai Gerakan 17 + 8, dan lantas mencoba “merangkum” kemarahan organik rakyat menjadi 17 tuntutan jangka pendek, dan 8 tuntutan jangka panjang. Kemarahan organik rakyat yang berasal dari pengalaman ketertindasan sehari-hari dikuantifikasi menjadi semata-mata 25 tuntutan, yang alih-alih mereka sebut sebagai 25 tuntutan, mereka memilih menyebutnya sebagai 17 + 8 tuntutan –merujuk pada tanggal 17 Agustus yang merupakan hari kemerdekaan Negara Indonesia, melambangkan nasionalisme semu.
Tentu, atas nama kebebasan berpendapat yang sama-sama kita percayai, hal tersebut sah-sah saja untuk dilakukan, apalagi secara substansi, tuntutan-tuntutan itu menyangkut aspirasi soal situasi politik dan penyelenggaraan negara yang carut-marut. Akan tetapi, yang menjadi masalah adalah ketika gerakan tersebut tanpa malu-malu mengklaim bahwa tuntutan mereka adalah tuntutan rakyat. Setidak-tidaknya, klaim itu masih dapat kita lihat sampai sekarang di salah satu situs web organisasi afiliasi mereka yang menyatakan bahwa tuntutan mereka sebagai “17 + 8 Tuntutan Rakyat”. Hal yang sangat problematik, menyisakan banyak pertanyaan yang tidak terjawab, setidak-tidaknya:
- Siapa rakyat yang dimaksud?
- Jika jawabannya adalah seluruh rakyat, sejauh mana keterlibatan rakyat dalam penyusunan tuntutan-tuntutan yang katanya tuntutan rakyat tersebut?
- Apakah memungkinkan merangkum pendapat 270 juta rakyat Indonesia hanya dalam waktu kurang dari seminggu?
- Jika jawabannya mungkin, apakah memungkinkan merangkum seluruh pendapat yang didasari pengalaman-pengalaman valid rakyat menjadi hanya berjumlah 17 + 8, yang lebih merupakan angka yang dipilih untuk kepentingan kampanye dan estetika semata?
Dua pertanyaan terakhir tentu merupakan pertanyaan retoris, sebab kita sama-sama tahu bahwa jawabannya adalah tidak mungkin. Dan dengan demikian, maka hal itu akan melahirkan satu pertanyaan etis:
- Apakah etis menyebut tuntutan 17+8 ini sebagai tuntutan rakyat?
Di tengah problematiknya gerakan tersebut, entah bagaimana, sejurus kemudian hampir semua pemberitaan di media massa maupun diskursus di media sosial seolah berputar hanya pada narasi atau aktivitas mereka. Hal ini tentu sesuatu yang tidak mengagetkan, mengingat mereka adalah sekelompok influencer yang memiliki daya tarik untuk pemberitaan media massa dan eksposur di media sosial, serta memiliki pengaruh terhadap opini publik. Sialnya, di tengah pelarangan bagi media massa untuk meliput soal demonstrasi, media sosial menjadi salah satu pusat informasi terkait aksi-aksi yang terjadi di berbagai kota. Namun, dengan adanya sorotan yang terasa terpusat pada Gerakan 17 + 8, yang lainnya terasa tenggelam, dan diskursus soal perlawanan seolah-olah terwakili oleh konten-konten media sosial mengenai mereka. Serta-merta, Gerakan 17 + 8 menjadi wajah baru keterwakilan gerakan perlawanan rakyat.
Sontak, perlawanan rakyat yang organik dan sarat kemarahan digeser menjadi gerakan sopan nan normatif. Gerakan perlawanan rakyat yang semula dimulai dengan kemarahan pada DPR yang dirasa sudah tidak lagi mewakili rakyat, kemudian seolah terwakili oleh Gerakan 17 + 8 yang mengklaim sebagai perwakilan baru rakyat kemudian justru malah mengirimkan tuntutan mereka ke DPR. Gerakan perlawanan rakyat yang semula diwarnai dengan kemarahan yang sarat dengan teriakan “Bubarkan DPR”, lantas direpresentasikan oleh Gerakan 17 + 8 yang mengklaim mewakili rakyat malah melihat DPR sebagai kanal perubahan, yang secara otomatis merusak upaya mendelegitimasi keterwakilan DPR, sebagaimana dengan susah payah dilakukan oleh rakyat yang katanya mereka wakili. Fakta-fakta kontradiktif antara yang mewakili dengan yang diwakili.
Tuntutan-tuntutan yang diberikan Gerakan 17 + 8 kepada DPR disertai dengan tenggat waktu. Konon, mereka meminta agar 17 tuntutan jangka pendek dipenuhi maksimal pada 05 September 2025, dan 8 tuntutan jangka panjang pada 31 Agustus 2026. Pada 05 September 2025, DPR mengumumkan 6 poin putusan, yang pada hakikatnya hanya mengabulkan 3 dari 17 tuntutan jangka pendek itu, dan sebagian dari mereka kemudian memaknainya sebagai “kemenangan kecil”, dan yang selanjutnya terjadi adalah de-eskalasi, bersamaan dengan “kemenangan kecil’ versi mereka disertai kekalahan yang jauh lebih besar yang dialami oleh rakyat: gerakan perlawanan rakyat yang mati terlalu dini.
Dan fakta-fakta ini seharusnya lebih dari cukup untuk kembali lagi menegaskan tesis lama anarkisme bahwa keterwakilan tidak pernah cukup untuk menjadi solusi atau jawaban dari apapun.
Yang Masih Terjadi Sampai Hari Ini
Salah satu dari 17 + 8 tuntutan adalah agar Negara membebaskan para demonstran yang telah ditangkap serta menghentikan kriminalisasi terhadap para demonstran, dan tuntutan ini tidak termasuk dalam “kemenangan kecil” versi mereka. Hingga hari ini, ribuan orang telah ditangkap karena keterlibatan mereka dalam gelombang perlawanan. Saat ini, Negara dengan bangga menyatakan bahwa 997 di antaranya masih ditahan. Beberapa organisasi masyarakat sipil mencatat setidak-tidaknya masih ada 2 orang yang dinyatakan hilang dan belum juga ditemukan, dan tidak ada apapun yang dilakukan oleh wajah baru keterwakilan rakyat itu.
Sejak penangkapan besar-besaran itu pula, perburuan terhadap para anarkis juga masih dilakukan hingga sekarang. Pada September 2025, setidak-tidaknya sudah ada 42 individu yang teridentifikasi anarkis ditangkap. Beberapa jaringan anarkis juga melaporkan bahwa ada beberapa individu yang hari ini masih menjadi pelarian dalam upaya menyelamatkan diri.
Negara mengklasifikasi para demonstran yang ditangkap ke dalam tiga klaster: penghasut, perusuh, dan penjarah. Mereka yang dilabel sebagai penghasut masih dalam kondisi yang sedikit lebih baik sebab mereka masih disorot lewat pemberitaan-pemberitaan media massa dan dibela atas nama kebebasan berpendapat. Sialnya, para anarkis dan ratusan demonstran lainnya yang ditangkap, kebanyakan dimasukkan dalam klaster perusuh dan penjarah. Mereka dilabel sebagai kriminal, dan oleh karenanya mendapat tempat yang kurang baik dalam pemberitaan maupun persepsi publik.
Perburuan para anarkis ini, bersama dengan hampir seribu orang yang masih ditangkap dan mereka yang masih dalam pelarian, dengan sendirinya menambah panjang daftar kekalahan rakyat Indonesia, yang diawali oleh 10 orang yang telah mati dibunuh Negara.
Untuk Nama-nama yang Patut Kita Kenang
Tulisan ini adalah bentuk solidaritas bagi Affan Kurniawan, Andika Lutfi Falah, Iko Juliant Junior, Muhammad Akbar Basri, Rheza Sendy Pratama, Rusdamdiansyah, Saiful Akbar, Sarina Wati, Septinus Sesa, dan Sumari, yang harus abadi dalam ingatan kita sebagai nama, bukan sekadar angka.
Nama-nama ini, pada akhirnya tidak sia-sia. Sekurang-kurangnya, nama-nama ini menjadi monumen kegagalan Negara menjalankan peran yang mereka tentukan sendiri dalam teori-teori klasiknya: untuk melindungi rakyatnya sendiri. Faktanya, mereka mati dibunuh Negara, yang secara berulang selalu menghadapi rakyatnya dengan kekerasan, tak peduli betapapun pemerintahnya silih berganti. Dalam suara yang paling parau, kematian mereka seolah berteriak bahwa konsep good governance adalah ilusi semata.
Nama-nama ini juga patut dikenang sebagai orang-orang yang menguak bahwa teori-teori klasik negara demokratis telah sepenuhnya terbukti gagal, sebab mereka mati dalam gelombang perlawanan terhadap DPR, entitas yang seharusnya menjadi penyeimbang kekuasaan eksekutif, namun dalam praktiknya telah terang-terangan menunjukkan keberpihakannya kepada rezim sebab partai-partai politik yang menguasai kursi parlemen hampir seluruhnya adalah partai pendukung pemerintah. Oleh karenanya, peran DPR untuk menjadi anjing penjaga jalannya kekuasaan dengan sendirinya akan selalu tidak berjalan dengan semestinya sebagaimana tertulis dalam teori-teori tersebut.
Dan pada akhirnya, untuk nama-nama ini pula, kita perlu mengarahkan tangan kita ke hidung keterwakilan-isme, bahwa sepanjang sejarah, mereka telah selalu gagal, dan kegagalan-kegagalan yang mereka lahirkan seringkali menuntut harga yang kepalang mahal.