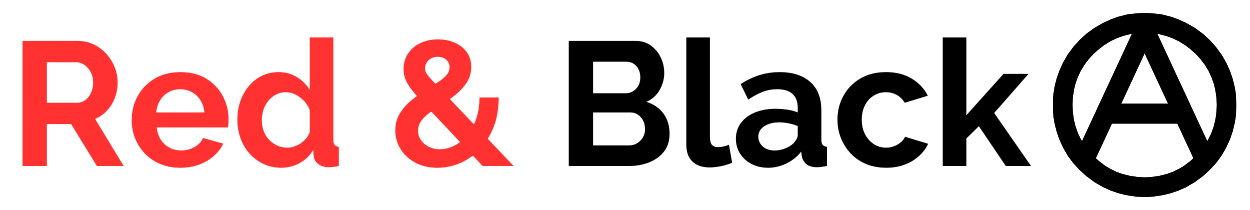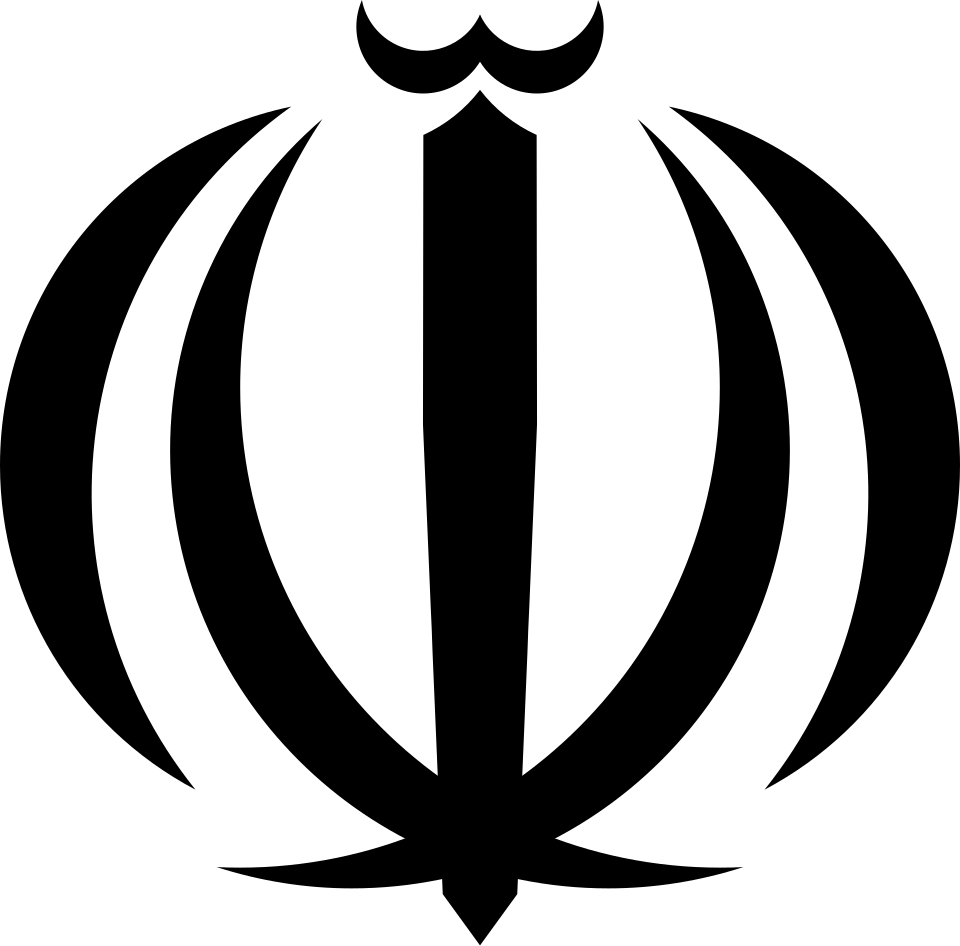Bencana Ekologis di Sumatera: Penghambaan Total Negara pada Kepentingan Kapital

Banyak orang bersepakat bahwa banjir bandang dan longsor yang terjadi di tiga provinsi di Sumatera bukanlah bencana alam, melainkan bencana ekologis. Sebab, alam tak bisa disalahkan begitu saja, ketika keputusan politik Negara lah yang menyebabkan bencana ini terjadi, membuat bencana ini tak bisa ditanggulangi, sehingga ribuan kehidupan tak bisa diselamatkan.
Kala bencana itu melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November lalu, banyak orang, termasuk anak-anak dan lansia, harus bertahan berhari-hari di atap rumah mereka tanpa makan dan minum menunggu evakuasi datang. Berdasarkan data per 20 Desember 2025, 1.090 orang meninggal, 186 belum ditemukan, serta 510.528 orang hidup dalam pengungsian. Sebelumnya, 4 desa di Aceh telah dinyatakan hilang. Kesemuanya dapat kita lihat sebagai hasil dari rentetan keputusan politik Negara yang semakin menunjukkan wajah aslinya.
Organisasi masyarakat sipil yang fokus pada lingkungan hidup, WALHI Sumatera Utara, menyampaikan bahwa setidak-tidaknya ada tujuh perusahaan yang seharusnya paling bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang menjadi penyebab bencana ekologis ini. Praktik bisnis industri ekstraktif yang dilakukan tujuh perusahaan itu, menurut WALHI, menyebabkan kerusakan pada Ekosistem Batang Toru di Provinsi Sumatera Utara yang merupakan bentang hutan terakhir yang ada di sana. Kerusakan yang terjadi di sana menyebabkan keberadaan ekosistem tersebut sebagai hutan penyangga hidrologis terus terkikis.
Keberadaan tujuh perusahaan itu, termasuk kerusakan lingkungan yang dihasilkan praktik eksploitasi industri ekstraktif mereka atas lingkungan, tak lepas dari peran Negara sebagai pemberi izinnya. Dan praktik-praktik tersebut tentu tidak terjadi hanya dalam satu-dua hari belakangan saja, melainkan sudah terjadi entah berapa lama. Dalam kerangka hak asasi manusia, ada dua jenis pelanggaran yang bisa dilakukan Negara, yakni pelanggaran langsung atau by commission dan pelanggaran tak langsung atau by omission. Jenis pelanggaran yang terakhir umumnya berupa pembiaran, dan itu yang telah dilakukan Negara dalam konteks ini.
Deforestasi telah menjadi kritik gerakan masyarakat sipil terhadap bagaimana Negara mengelola lingkungan hidup. Hutan yang ditebangi secara brutal dan membabi-buta untuk dialihfungsikan sebagai kebun sawit telah begitu banyak dikritik. Dalam sebuah kesempatan, Prabowo selaku Kepala Negara menyatakan tak perlu khawatir dengan deforestasi, karena menurutnya, “pohon sawit juga pohon, ada daunnya.” Sebuah pernyataan yang terlampau bodoh untuk dinyatakan oleh seorang presiden, membandingkan hutan dengan kebun luas yang hanya ditanami satu jenis tanaman saja (monokultur), apalagi saat tanaman yang dimaksud tidak memiliki kemampuan menyerap air dan menjaga tanah dari longsor yang baik.
Namun, kebodohan ini rupanya masuk akal-masuk akal saja bagi Negara yang begitu membela sawit sedemikian rupa untuk sebuah alasan: penghambaan total pada kepentingan kapital.
Pada 2022 saja, data Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengeluarkan data bahwa dari total seluruh pelaku usaha sawit di Indonesia, 0.07% nya adalah perusahaan sawit, dengan besaran lahan yang dikuasai mencapai sekitar 54,52%. Sementara, sekitar 41,35% lainnya diolah oleh pekebun sawit kecil. Sisanya, dikelola BUMN. Data ini menunjukan ketimpangan yang teramat besar dalam soal konsesi lahan sawit. Pemilik kapital besar diberikan porsi lebih dari setengah dari total lahan sawit yang ada, hanya untuk segelintir orang, sementara rakyat kecil diberikan jauh di bawah 50%.
Berdasarkan data Peta Sawit Nasional yang dirilis Badan Informasi Geospasial, pada 2023 saja, total besaran lahan sawit di Indonesia mencapai 17,3 juta hektar. Mengacu pada data ini, tandanya lebih dari 8,5 juta hektar lahan dikuasai oleh beberapa perusahaan yang dimiliki segelintir orang, di antaranya adalah Arsari Group milik Hasjim Djojohadikusumo yang merupakan adik dari Presiden Prabowo.
Tak hanya berbicara mengenai timpangnya konsesi lahan sawit, dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan-perusahaan sawit inipun melakukan praktik-praktik yang meminggirkan HAM dan sarat eksploitasi besar-besaran atas lingkungan. Sebagai gambaran, pada 2024 WALHI memaparkan salah satu perusahaan sawit terbesar di Indonesia yakni Astra Agro Lestari (AAL) kerap melakukan pelanggaran lingkungan hidup dan tata kelola, seperti penanaman sawit ilegal di dalam kawasan hutan Indonesia.
Dalam temuannya, WALHI menyatakan 17 konsesi kelapa sawit anak perusahaan AAL tumpang tindih dengan 17.664 hektar kawasan hutan Indonesia. Selain itu, WALHI juga menyatakan 1.100 hektar lahan sawit yang dikelola AAL ilegal, dan 3 anak perusahaan AAL beroperasi tanpa izin. Mereka juga kerap melakukan intimidasi terhadap pembela HAM di sektor lingkungan.
Timpangnya kepemilikan lahan sawit, buruknya praktik dalam menjalankan praktik, dan dampak lingkungan yang telah terjadi tak jua membuat Negara lebih baik dalam mengambil keputusan. Nyatanya, baru-baru ini Prabowo menyerukan pembukaan lahan-lahan sawit baru di Papua. Pernyataan yang menunjukkan sikap politik yang teramat biadab, di tengah bencana yang masih belum juga diselesaikan dengan baik. Ribuan korban yang telah meninggal, ratusan yang masih hilang, dan jutaan lain yang terdampak seolah masih dinilai belum cukup.
Belum Cukup Korban untuk Jadi Bencana Nasional
“Ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali,” kata Prabowo dalam sebuah pernyataan publiknya menanggapi desakan korban terdampak dan masyarakat agar bencana yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ditetapkan sebagai bencana nasional. Menggunakan pendekatan cara berpikir yang sama, maka lebih dari seribu orang yang telah meregang nyawa hanya dilihat sebagai “1.090 dari 270.000.000 warga.” Bila nyawa manusia hanya dilihat dengan pendekatan kuantitatif, maka perlu berapa nyawa lagi yang mati agar situasi ini ditetapkan sebagai bencana nasional?
Pertanyaan itu tentu pertanyaan retoris, sebagai wujud kemarahan –atau bahkan frustasi– atas fakta bahwa pemerintah begitu ngotot menolak menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional, meskipun kenyataannya masih begitu banyak korban terdampak, terutama di Provinsi Aceh, yang masih belum mendapat bantuan yang berarti dari Negara.
Bahkan setelah hingga tiga minggu berselang, beberapa reportase jurnalistik menyampaikan bahwa masih begitu banyak korban kesulitan untuk makan. Anak-anak kecil kelaparan. Para korban menyatakan mereka masih hidup dalam keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, belum menyoal sulitnya akses, rusaknya infrastruktur, jalan-jalan penghubung, keterbatasan listrik, dan sinyal untuk komunikasi. Salah satu reportase yang menggambarkan kesulitan korban di Aceh Tamiang, sebuah daerah di Provinsi aceh yang paling parah terdampak, kemudian di-takedown. Banyak pihak menduga ada tekanan dari Negara terhadap institusi pers itu.
Sedari awal, para korban mendapatkan bantuan dari solidaritas warga dari seluruh penjuru wilayah Indonesia. Berbagai pihak bahu membahu mengumpulkan donasi untuk kemudian disalurkan ke lokasi-lokasi bencana. Bantuan-bantuan ini murni diinisiasi oleh warga. Tak sedikit pula orang-orang melibatkan diri sebagai relawan kemanusiaan. Secara signifikan, gotong royong betul-betul berdampak pada kelangsungan hidup para korban sebab ada kesadaran bahwa Negara tak bisa diandalkan.
Di tengah keterbatasan kebutuhan hidup yang dialami para korban karena Negara lamban bergerak sehingga para korban menggantungkan hidup pada solidaritas antar warga, Negara malah melihat solidaritas antar warga itu sebagai ancaman dan kemudian mempersulit prosedurnya dengan mengeluarkan ketetapan bahwa setiap bantuan atau donasi yang diinisiasi oleh warga harus mendapat izin dari pemerintah terlebih dahulu. Hal ini dibarengi dengan penolakan pemerintah pusat terhadap bantuan dari komunitas internasional. Dalam beberapa pemberitaan, Prabowo menyatakan Indonesia tidak perlu bantuan ketika ditanya oleh beberapa kepala negara lain soal bencana yang terjadi. Bahkan, pemerintah sempat akan mengembalikan bantuan 30 ton beras dari Uni Emirat Arab, meskipun belakangan pemerintah menyatakan bantuan itu akan disalurkan kepada korban.
Dugaan pembredelan berita tentang situasi terkini yang dialami korban di Aceh, bersikerasnya Negara tak mau mengakui situasi ini sebagai bencana nasional, pernyataan presiden kepada komunitas internasional bahwa pemerintah tidak perlu bantuan dalam menangani bencana yang terjadi, hingga pemberlakuan izin pada warga yang ingin menggalang bantuan dan donasi, dapat dilihat dalam nuansa Negara hendak mempertahankan citra bahwa situasi masih baik-baik saja, kendatipun ribuan orang telah meninggal, ratusan orang masih hilang dan belum ditemukan hingga kini, ribuan rumah rusak, jutaan warga terdampak dan hidup dalam pengungsian, dan banyak dari mereka masih hidup dalam keterbatasan kebutuhan hidup sehari-hari pasca bencana.
Penderitaan-penderitaan yang dialami korban diabaikan. Nyawa-nyawa dilihat sebagai semata-mata angka. Kesemuanya dilakukan Negara untuk sekadar kesan belaka: semua masih terkendali dan situasi nasional masih stabil.
Stabilitas Nasional: Alasan Keberulangan Kejahatan Negara
Bila memang stabilitas nasional menjadi alasan, maka kejahatan Negara yang terjadi dalam seluruh rangkaian peristiwa bencana, dari musabab hingga penanggulangannya, menjadi tidak mengagetkan. Sepanjang sejarah republik, frasa “stabilitas nasional” hampir selalu menjadi alasan di balik sejumlah kejahatan yang dilakukan Negara sejak berpuluh tahun lampau.
Rezim Orde baru di bawah kepemimpinan Soeharto tercatat melakukan belasan pelanggaran berat HAM yang sebagian besarnya dilakukan guna membangun imaji “stabilitas nasional”. Pembantaian 500.000 - 3.000.000 orang yang dianggap terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia pada 1965 - 1966, misalnya, dilakukan untuk membasmi musuh politik Soeharto. Tak lama setelahnya, ketika situasi dinyatakan sudah stabil, Freeport menandatangani kontrak untuk berinvestasi di Indonesia, membuka jalan untuk terus dilakukannya eksploitasi sumber daya alam di Papua yang masih terus berlangsung hingga detik ini.
Pada medio 1980-an, rezim yang sama melangsungkan, operasi pembunuhan besar-besaran terhadap orang-orang yang dianggap kriminal. Tanpa proses pembuktian mereka betul kriminal, orang-orang yang bertato dan berambut gondrong dibunuh. Mayatnya bergelimpangan di jalan-jalan. Sejumlah sumber menyatakan korbannya berkisar antara 2.000 hingga 8.000 orang. Peristiwa ini dikenal dengan istilah Petrus atau Penembakan Misterius, dan tujuan utamanya adalah demi menciptakan stabilitas nasional, yang menjadikan keamanan atau ketertiban nasional sebagai prasyaratnya.
Pada 1989, rezim Orde Baru kembali membantai sekelompok orang yang dianggap Islamis di Talangsari, Lampung, yang karena keyakinannya oleh Negara dilihat sebagai pengganggu stabilitas politik, sebab tidak sesuai dengan tafsir tunggal Negara atas Pancasila yang konon merupakan ideologi tunggal Negara. Komnas HAM mencatat 130 orang tewas.
Tiga contoh kasus di atas hanya sebagian dari masih banyak lagi kejahatan yang dilakukan Negara dalam rangka menjaga stabilitas nasional. Untuk lebih lengkapnya, dapat dibaca di artikel sebelumnya di website ini yang berjudul: #IndonesiaGelap: Kekerasan Negara Lintas Zaman. Kejahatan-kejahatan ini tetap berlangsung meskipun pemerintahannya berganti. Bagi Negara, stabilitas nasional begitu perlu dibela mati-matian, sebab ia adalah syarat mutlak masuknya investasi, yang dalam bahasa lain, kapital.
Bendera Putih
Pada 18 Desember 2025, sejumlah elemen masyarakat di kota Banda Aceh, ibukota Provinsi Aceh, melakukan demonstrasi mengibarkan bendera putih. Sejak berhari-hari sebelumnya, masyarakat di berbagai kota di Provinsi Aceh telah beramai-ramai mengibarkan bendera putih di banyak penjuru.
Bagi warga Aceh, pengibaran bendera putih ini adalah bentuk pengakuan bahwa mereka sudah terlampau lelah, dan butuh bantuan. Tiga pekan berlalu, mereka masih belum juga mendapatkan kebutuhan pokok yang memadai. Di tengah buruknya penanganan bantuan karena begitu banyak akses transportasi yang terputus, berkibarnya bendera-bendera putih di banyak wilayah di Aceh seperti menjadi antitesis dari pernyataan Negara bahwa semua terkendali.
Menutup tahun dengan mengibarkan bendera putih, warga Aceh berteriak butuh bantuan di kala Negara tak bisa diandalkan. Bendera putih memang identik dengan simbol menyerah. Tapi, di Aceh, bendera putih menjadi simbol keberanian untuk menyatakan bahwa Aceh sedang tidak baik-baik saja –keberanian yang sampai hari ini tak dimiliki oleh Negara. Dimulai dari Aceh, bendera putih menjadi simbol perlawanan terhadap ilusi “stabilitas nasional” yang telah membunuh begitu banyak orang.