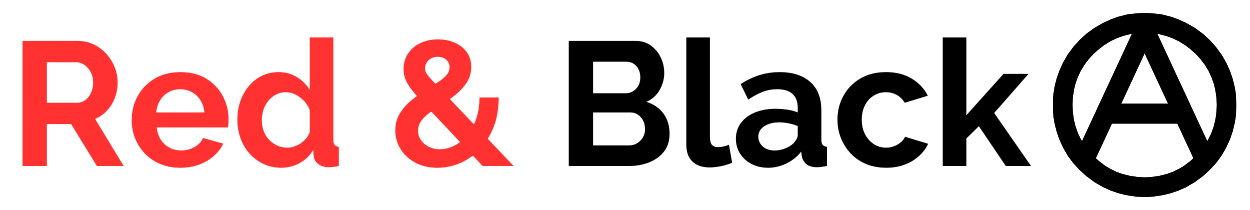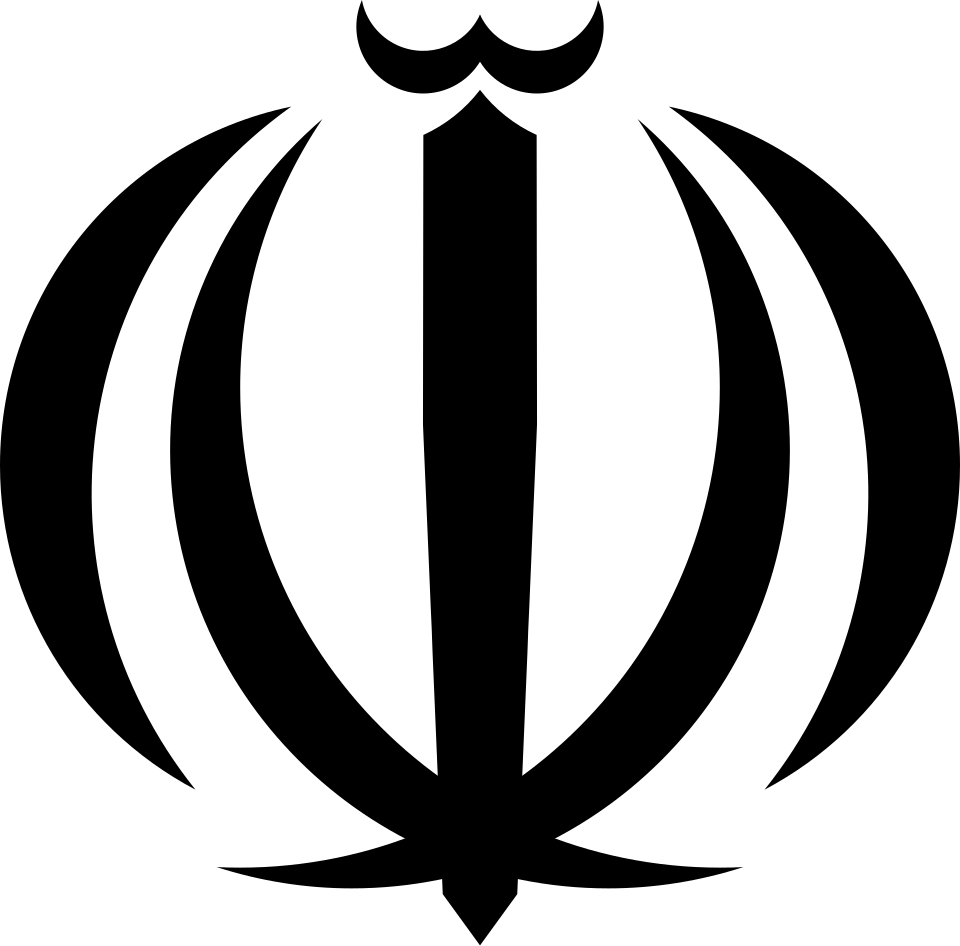Ilusi Batas Negara dan Diskriminasi terhadap Orang Tanpa Kewarganegaraan: Satu dari Banyak Alasan Kita Tidak Butuh Negara

Sekilas tentang Orang Tanpa Kewarganegaraan
Pada akhir 2019, United Nation High Commissioner on Refugees (UNHCR) mencatat 4,2 juta orang tanpa kewarganegaraan di seluruh dunia. Berselang tiga tahun, organisasi yang sama mencatat 4,4 juta orang tanpa kewarganegaraan di seluruh dunia. Fluktuatifnya jumlah orang tanpa kewarganegaraan yang tercatat menunjukkan ketidakpastian jumlah orang tanpa kewarganegaraan di seluruh dunia. UNHCR sendiri mengakui bahwa jumlah sebenarnya mungkin lebih dari 10 juta jiwa karena banyak yang tidak tercatat. Sedangkan, laporan Amnesty International memperkirakan angka yang lebih besar, yakni sekitar 15 juta orang di seluruh dunia.
Sekitar 40 persen dari total populasi orang tanpa kewarganegaraan secara global terdapat di kawasan Asia Pasifik, di mana kawasan Asia Tenggara secara spesifik menjadi kawasan terbanyak tempat keberadaan orang tanpa kewarganegaraan. Dengan lebih dari satu juta orang tanpa kewarganegaraan, orang-orang Rohingya dari Myanmar – yang kini telah tersebar di Myanmar, Bangladesh, Indonesia, dan negara-negara lainnya di kawasan – masih menjadi kasus terbanyak. UNHCR juga melaporkan adanya populasi orang tanpa kewarganegaraan di Thailand (475.009 jiwa), Malaysia (108.332 jiwa), Kamboja (57.444 jiwa), Vietnam (30.581 jiwa) dan Brunei Darussalam (20.863 jiwa). Lagi-lagi, jumlah sebenarnya kemungkinan besar jauh lebih tinggi daripada yang tercatat.
Orang tanpa kewarganegaraan adalah seseorang yang menurut hukum nasional tidak menikmati kewarganegaraan di negara mana pun. Ketiadaan kewarganegaraan ini berimplikasi pada tidak adanya ikatan hukum antara negara dan orang-orang tersebut.
Situasi ketiadaan kewarganegaraan seseorang dapat diklasifikasikan menjadi dua tipe, yakni de jure dan de facto. Orang tanpa kewarganegaraan secara de jure adalah mereka yang secara hukum tidak diakui sebagai warga negara di bawah undang-undang negara mana pun, sedangkan secara de facto, adalah mereka yang tidak mempunyai kewarganegaraan secara efektif. Mereka memiliki klaim kewarganegaraan di satu atau lebih negara, tetapi secara praktis tidak dapat menikmati hak-haknya sebagai warga negara, misalnya mereka yang kini berstatus sebagai pengungsi atau pencari suaka.
Komunitas internasional pun telah melihat problem situasi ketiadaan berkewarganegaraan ini sebagai masalah global bersama. Setidaknya tercatat dua instrumen HAM internasional menyoal keberadaan orang tanpa kewarganegaraan ini, yakni Konvensi 1954 tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan, dan Konvensi 1961 tentang Pengurangan Kondisi Tanpa Kewarganegaraan. Negara-negara Asia Tenggara tercatat memiliki rekam jejak yang buruk dalam meratifikasi konvensi-konvensi tersebut. Hanya Filipina yang telah meratifikasi Konvensi 1954, dan tidak ada satupun negara yang telah menjadi negara pihak Konvensi 1961.
Ketiadaan Kewarganegaraan di Indonesia: Tinjauan De Jure
Menurut Undang-undang No. 12 tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, warga negara Indonesia adalah:
a) setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia; b) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia; c) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing; d) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia; e) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut; f) anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia; g) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia; h) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin; i) anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya; j) anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui; k) anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya; l) anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan; m) anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
Selain mengatur soal siapa-siapa saja yang dapat menjadi warga negaranya, UU No. 12/2006 juga menyebut asas-asas kewarganegaraan yang dianut Indonesia. Asas-asas kewarganegaraan umum yang terkandung dalam UU ini adalah:
- Asas ius sanguinis, asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran;
- Asas ius soli, asas yang secara terbatas menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini;
- Asas kewarganegaraan tunggal, asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang;
- Asas kewarganegaraan ganda terbatas, asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini.
Dengan demikian, hukum Indonesia tidak mengenal orang tanpa kewarganegaraan, sebab tidak ada regulasi yang mengatur dan memberikan perlindungan kepada orang tanpa kewarganegaraan.
Di bawah UU No. 12/2006, Indonesia hanya mengenal dua kategori, yakni warga negara Indonesia dan orang asing. Tandanya, undang-undang tersebut tidak mengakui orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Meskipun undang-undang tersebut menyatakan tentang kehilangan kewarganegaraan bagi orang Indonesia, tetapi masih belum jelas bagaimana pemerintah Indonesia dapat menangani seseorang yang kehilangan kewarganegaraan.
Orang dengan Risiko Tanpa Kewarganegaraan: Tinjauan De Facto
Orang tanpa kewarganegaraan, sekali lagi, diklasifikasikan secara de jure dan de facto. Selain secara de jure yang artinya seseorang tidak diakui kewarganegaraannya secara hukum oleh negara manapun, ada juga orang tanpa kewarganegaraan secara de facto yang sebetulnya (atau sebelumnya) memiliki kewarganegaraan, akan tetapi dalam praktiknya tidak mampu mengakses hak-haknya sebagai warga negara. Orang-orang ini dapat disebut sebagai orang dengan risiko tanpa kewarganegaraan.
Secara umum, banyak karakteristik komunitas yang berisiko dapat menjadi orang-orang tanpa kewarganegaraan. Dalam konteks Indonesia, beberapa di antaranya adalah:
a. Pengungsi dan/atau Pencari Suaka
Pengungsi adalah orang yang melarikan diri dari negaranya sendiri karena mereka menghadapi risiko pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan penganiayaan di sana. Risiko terhadap keselamatan dan kehidupan mereka begitu besar sehingga mereka merasa tidak punya pilihan selain pergi dan mencari keselamatan di luar negara mereka karena pemerintah mereka sendiri tidak dapat atau tidak akan melindungi mereka dari bahaya tersebut. Pengungsi memiliki hak atas perlindungan internasional.
Ada banyak alasan mengapa mungkin berbahaya bagi seseorang untuk tinggal di negara mereka sendiri. Misalnya, mereka melarikan diri dari kekerasan, perang, kelaparan, kemiskinan ekstrem, karena orientasi seksual atau gender mereka, atau dari konsekuensi perubahan iklim atau bencana alam lainnya. Seringkali alasan-alasan tersebut tidak berdiri sendiri, seseorang bisa saja menghadapi kombinasi dari keadaan sulit ini.
Secara umum, ada banyak karakteristik pengungsi. Pertama, para pengungsi yang keluar dari negaranya dengan alasan-alasan tertentu termasuk keamanan, dengan tujuan untuk mendapatkan kewarganegaraan baru. Pada dasarnya, secara legal komunitas dengan karakteristik ini masih dapat mengakses hak-hak dasarnya di negara asal mereka.
Hal tersebut berbeda dengan komunitas pengungsi jenis lainnya yang memang sudah tidak memiliki kewarganegaraan atau status kewarganegaraannya dicabut oleh negara asalnya. Situasi ini kemudian membuat mereka bahkan tidak lagi bisa mengakses hak-hak dasar mereka di negara asalnya, dan di saat yang bersamaan, mereka tidak memiliki payung hukum baru karena belum memiliki kewarganegaraan yang baru.
Komunitas-komunitas yang disebut dalam poin kedua di atas kemudian masih dapat mendapatkan perlindungan dari UNHCR setelah UNHCR menjalankan prosedur Penentuan Status Pengungsi atau Refugee Status Determination (RSD), yang dimulai dengan registrasi atau pendaftaran terhadap para pencari suaka. Setelah registrasi, UNHCR akan melakukan wawancara individual dengan masing – masing pencari suaka, dengan didampingi seorang penerjemah yang kompeten. Proses ini melahirkan keputusan yang beralasan yang menentukan apakah permintaan status pengungsi seseorang diterima atau ditolak dan memberikan masing – masing individu sebuah kesempatan (satu kali) untuk meminta banding apabila permohonannya ditolak.
Mereka yang kemudian ditolak status pengungsinya oleh UNHCR nantinya akan menjadi orang-orang dengan status penolakan akhir. Dengan tiadanya kewarganegaraan dari negara asal dan tiadanya pengakuan dari UNHCR, orang-orang dari kelompok ini menjadi orang-orang yang tidak memiliki payung hukum dan/atau perlindungan hukum sama sekali,
Komunitas Rohingya dari Myanmar adalah salah satu populasi orang tanpa kewarganegaraan terbesar di dunia. Data per September 2020, Sekitar 600.000 orang Rohingya masih tinggal di Myanmar, sementara lebih dari 900.000 Rohingya telah dipaksa melewati perbatasan ke Bangladesh untuk melarikan diri dari kekerasan, dan sejumlah lainnya melarikan diri ke negara-negara tetangga lainnya termasuk Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, juga Indonesia.
Data UNHCR per Mei 2022 mencatat ada 627 pengungsi yang berstatus tanpa kewarganegaraan di Indonesia. Keseluruh 627 orang itu berasal dari 6 negara, yakni Irak, Iran, Arab Saudi, Kuwait, Jepang, dan juga termasuk komunitas Rohingya dari Myanmar. Jumlahnya kini tentu sudah jauh meningkat, mengingat gelombang kedatangan besar-besaran pengungsi Rohingya di penghujung 2023 dan awal 2024.
UNHCR sendiri didirikan oleh Majelis Umum PBB (MU PBB) tahun 1951, meskipun Anggaran Dasarnya disetujui MU PBB sejak Desember 1950, dengan tugas UNHCR memberikan perlindungan internasional terhadap pengungsi yang termasuk wewenang UNHCR.
Mereka yang teridentifikasi sebagai pengungsi setelah melalui tahap RSD sebagaimana disebutkan di atas akan menerima perlindungan selama UNHCR mencarikan solusi jangka panjang, yang biasanya berupa penempatan di negara lain. Untuk tujuan ini, UNHCR berhubungan erat dengan negara – negara yang memiliki potensi untuk menerima pengungsi. Sampai dengan akhir Juli 2020, sebanyak 3.375 pencari suaka dan 10.278 pengungsi terdaftar di UNHCR Jakarta secara kumulatif.
b. Pekerja Migran Tidak Terdokumentasi
Seseorang yang pergi ke luar negeri tanpa terdokumentasi menjadi sangat rentan di negara tujuan maupun ketika ia pulang ke negara asalnya. Bisa saja, orang tersebut memiliki kewarganegaraan di negara asalnya. Akan tetapi, karena ia menjadi migran yang tidak terdokumentasi, ketika sampai di negara tujuan, ia tak memiliki jaminan hukum. Pertama, karena ia tidak tercatat secara resmi di negara asalnya sebagai migran, kedua, karena di negara tujuan ia tidak berada di bawah jaminan hukum yang mengikat secara bilateral. Dalam situasi ini, orang tersebut berada dalam kerentanan yang sama seperti orang-orang yang tidak berkewarganegaraan.
Kerentanan itu juga bisa jadi diperparah dengan kondisi di mana keberadaan seorang pekerja migran yang tidak terdokumentasi di negara tujuannya sudah terlalu lama sehingga ia tidak memperbaharui kewarganegaraannya di negara asalnya, sehingga ia menjadi orang tanpa kewarganegaraan.
Dalam praktiknya, seringkali migran yang tidak terdokumentasi menikah di negara tujuannya sehingga terjadi perkawinan campur. Ketika mereka mempunyai anak, seringkali sang anak tidak dapat memiliki dokumentasi sehingga lahir tanpa kewarganegaraan. Di Indonesia, dalam UU No. 12/2006 sebenarnya terdapat pengaturan yang memungkinkan anak dari pasangan perkawinan campur memiliki kewarganegaraan.
Dalam praktiknya, orang-orang yang melakukan perkawinan campur dan memiliki anak kesulitan mengurus dokumen anaknya dalam hal administrasi kewarganegaraan yang kemudian berimplikasi pada penikmatan hak-hak lainnya.
Ketiadaan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia
Meskipun hanya Filipina yang baru meratifikasi Konvensi 1954 dan tidak ada satu negarapun di Asia Tenggara yang telah meratifikasi Konvensi 1961, instrumen-instrumen HAM lain seperti Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, dan Konvensi Hak Anak, menjamin poin penting perlindungan terhadap hak-hak orang tanpa kewarganegaraan, dan instrumen-instrumen tersebut sudah lebih banyak diratifikasi di kawasan. Deklarasi HAM ASEAN juga menjamin hal tersebut. Pasal 18 deklarasi tersebut menyatakan “setiap orang berhak atas kewarganegaraan sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang.”
Minimnya regulasi di tingkat internasional maupun regional yang mengatur tentang ketiadaan kewarganegaraan ini pada akhirnya berujung pada diskriminasi HAM khususnya terkait akses dan penikmatan HAM bagi orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan tersebut. HAM sebetulnya memiliki asas universalitas, di mana hak-hak universal ini melekat pada semua orang, terlepas dari kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, warna kulit, agama, bahasa, atau status lainnya. Mulai dari yang paling mendasar - hak untuk hidup - hingga yang membuat hidup layak untuk dijalani, seperti hak atas makanan, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan kebebasan.
Dalam HAM sendiri dikenal konsep pengemban kewajiban (duty-bearer) dan pemangku hak (rights-holder). Mengingat sifat universalitas hak asasi manusia, setiap individu adalah pemegang hak dan berhak untuk hak yang sama tanpa perbedaan. Sedangkan, pengemban kewajiban terutama adalah aktor negara di semua tingkatan, yang berkewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia.
Prinsip HAM yang kemudian telah merumuskan setiap manusia sebagai pemangku hak dan negara-negara sebagai pengemban kewajiban, disertai dengan prinsip universalitasnya yang menegaskan bahwa HAM melekat pada setiap individu tanpa terkecuali termasuk tanpa membedakan kebangsaannya, menegaskan bahwa sesungguhnya orang-orang tanpa kewarganegaraan memiliki hak yang sama besarnya dengan mereka yang berkewarganegaraan untuk dijamin oleh Negara manapun akses dan penikmatan mereka atas HAM.
Sebagai negara anggota Dewan HAM PBB dan negara pihak atas 9 dari 10 instrumen HAM internasional, Indonesia seharusnya berpegang teguh pada asas universalitas HAM di mana negara sebagai duty-bearer harusnya menjalankan 4 fungsinya dalam rangka pemenuhan, penghormatan, perlindungan dan pemajuan HAM bagi seluruh right-holders, termasuk orang-orang tanpa kewarganegaraan, juga orang-orang dengan risiko tanpa kewarganegaraan.
Diskriminasi terhadap Orang Tanpa Kewarganegaraan: Dampak Ilusi Batas Negara
Di seluruh dunia, keberadaan negara selalu menjadi akar dari masalah-masalah pelik lainnya sepanjang sejarah peradaban. Invasi atas nama kolonialisme berabad-abad lalu, perang pengaruh sepanjang Perang Dunia I, Perang Dunia II dan Perang Dingin yang menghantarkan jutaan orang ke kematian adalah contoh masalah di masa lalu yang dilahirkan keberadaan entitas bernama negara.
Hari-hari ini, kita diperhadapkan pada masalah-masalah baru yang melahirkan kejahatan terhadap kemanusiaan yang tak kalah mengerikan. Genosida besar-besaran atas bangsa Palestina oleh Israel, invasi Rusia atas Ukraina, maupun genosida terhadap bangsa Rohingya di Myanmar adalah beberapa contohnya. Terkhusus Rohingya, alasan terjadinya genosida atas mereka adalah ulah negara Myanmar itu sendiri yang mengeksklusi etnis Rohingya dari daftar 135 kelompok etnis yang diakui negara lewat pengesahan Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982. Dalam undang-undang tersebut, Myanmar secara terang-terangan tidak mengakui mereka sebagai warga negara Myanmar.
Masalah lain yang muncul dari keberadaan sebuah entitas bernama negara adalah keberadaan orang tanpa kewarganegaraan. Jika dibalik, maka dapat kita lihat, akar masalah dari keberadaan orang-orang tanpa kewarganegaraan adalah keberadaan negara itu sendiri, dan hal itu selalu melahirkan masalah-masalah lain di kemudian hari, yakni kehidupan mereka yang disebut sebagai orang-orang tanpa kewarganegaraan.
Riset berjudul “Pemetaan Situasi Orang dengan Risiko tanpa Kewarganegaraan di Indonesia” oleh Human Rights Working Group (HRWG) dan SUAKA menemukan adanya beberapa keterbatasan komunitas orang dengan risiko tanpa kewarganegaraan dalam mengakses penikmatan hak-hak dasarnya. Riset ini berfokus pada kehidupan komunitas pengungsi Rohingya, orang dalam status penolakan akhir dari UNHCR dan hidup mandiri, keluarga perkawinan campuran yang salah satu pasangan atau keduanya tidak memiliki dokumentasi kependudukan, dan keluarga perkawinan campuran yang memiliki anak-anak yang lahir di Indonesia dan belum terdokumentasi.
Ketiadaan kewarganegaraan yang dialami komunitas ini melahirkan begitu banyak pelanggaran atas hak-hak mendasar mereka. Setidak-tidaknya, ada beberapa hak yang tidak dapat dinikmati dengan baik oleh orang tanpa kewarganegaraan ini, yakni:
- Hak Atas Pendidikan
Keleluasaan untuk mengakses pendidikan mengharuskan adanya dokumentasi kependudukan. Hal ini bukanlah hal yang mudah didapatkan oleh orang dengan risiko tanpa kewarganegaraan. Alasan administratif sering dipakai sebagai hambatan bagi pengungsi atau orang tanpa kewarganegaraan untuk mendaftarkan anak-anak mereka dalam pendidikan formal.
Anak-anak yang dapat mengakses pendidikan formal cenderung bersekolah di sekolah swasta karena keringanan dalam persyaratan dokumen, tidak seperti di sekolah negeri. Terlebih bagi mereka yang tidak memiliki identitas apapun, hanya bisa menerima pengajaran di rumah oleh orang tua atau pengajaran informal yang umumnya tidak sesuai dengan kurikulum manapun.
Selain bahwa praktik ini menunjukkan bahwa hak anak untuk mengakses pendidikan terbatas dan anak-anak terhalang untuk menentukan pilihan mereka sendiri semata-mata karena identitas mereka sendiri dan identitas orang tua, hal ini juga menjadi sulit karena adanya keterbatasan bagi orang tanpa kewarganegaraan untuk mendapatkan pekerjaan, sementara sekolah swasta atau sekolah di rumah membutuhkan biaya yang mahal.
- Hak Atas Pekerjaan
Pengungsi atau pencari suaka yang telah mendapatkan status pengungsi dari UNHCR lewat mekanisme RSD dimungkinkan untuk mendapatkan bantuan logistik dan/atau ekonomi dari UNHCR. Akan tetapi, tidak dengan para pengungsi yang sudah mendapatkan penolakan akhir dari UNHCR, sebab orang tanpa kewarganegaraan tidak diizinkan secara hukum untuk bekerja di Indonesia.
Hak untuk bekerja sebagai salah satu bentuk penghidupan tertuang dan dijamin di dalam Konvensi 1951. Belum diratifikasinya Konvensi 1951 membuat Indonesia tidak berkewajiban menyediakan lapangan kerja bagi para pengungsi, sedangkan UNHCR dalam praktiknya tidak selalu dapat memberikan status pengungsi melalui mekanisme RSD kepada seluruh pengungsi.
Selain itu, berdasarkan peraturan pemerintah No. 48 tahun 2021, hak untuk bekerja bagi pengungsi secara hukum harus mengikuti peraturan yang berlaku terkait dengan orang asing, termasuk harus memiliki KITAS atau KITAP atau visa kerja, yang tidak memungkinkan bagi orang tanpa kewarganegaraan maupun orang dengan risiko tanpa kewarganegaraan.
Situasi ini membuat orang tanpa kewarganegaraan kesulitan menemukan cara bertahan hidup. Umumnya, mereka awalnya mengandalkan kiriman uang dari saudara atau teman mereka di luar Indonesia, tetapi sumber pendapatan itu tidak bertahan lama. Situasi ini juga kemudian secara signifikan berdampak pada situasi lain yang berdampak secara krusial bagi kehidupan mereka, salah satunya adalah soal kesehatan.
- Hak Atas Kesehatan
Selain kondisi kesehatan yang rentan akibat kualitas hidup yang tidak memadai sebagai akibat dari kondisi ekonomi karena tidak diperbolehkan bekerja, ketiadaan dokumen terkait kewarganegaraan merupakan salah satu penyebab paling signifikan untuk dapat menerima layanan kesehatan sebagai dampak dari kemampuan mereka untuk berobat secara finansial.
Mereka harus mengeluarkan secara mandiri biaya-biaya yang muncul, mencakup biaya tindakan, konsultasi, obat hingga transportasi. Walaupun Puskesmas dapat diakses dengan murah dan mudah, namun tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk perawatan lanjutan. Sementara, hanya orang-orang yang dianggap memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pendampingan kesehatan oleh IOM, UNHCR atau lembaga amal lainnya, salah satunya adalah dengan memiliki kartu UNHCR atau memenuhi kriteria ‘darurat‘ yang ditetapkan oleh masing-masing lembaga.
- Hak Atas Informasi
Di era digital, hak atas informasi berkaitan erat dan tidak terpisahkan dengan akses atas internet. Sayangnya, orang tanpa kewarganegaraan maupun orang dalam risiko tanpa kewarganegaraan menghadapi kesulitan untuk mengakses internet menggunakan ponsel mereka. Registrasi nomor ponsel Indonesia memerlukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang hanya tersedia untuk Warga Negara Indonesia. Registrasi nomor telepon dengan nomor identifikasi paspor juga tidak memungkinkan bagi mereka.
Situasi keberadaan orang tanpa kewarganegaraan (termasuk di dalamnya, di saat yang bersamaan, orang dengan kewarganegaraan) disebabkan karena adanya negara yang memberlakukan batas-batasnya.
Komunitas masyarakat yang hidup di perbatasan Sangir, Indonesia dan Filipina di utara Sulawesi, misalnya, adalah contoh konkret bagaimana batas-batas negara modern menjadi penyebab munculnya kondisi ketiadaan kewarganegaraan. Data UNHCR menyebutkan, populasi komunitas ini berjumlah sekitar 3.000-an orang tanpa kewarganegaraan, yang sudah secara turun-temurun tinggal di wilayah tersebut jauh sebelum munculnya batas negara Indonesia dan Filipina. Pemerintah Indonesia kemudian menyediakan mekanisme untuk mengakomodir mereka yang ingin menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Dari jumlah +- 3.000 jiwa tersebut, 1.400 di antaranya sudah bersedia menjadi WNI. Meskipun demikian, dari 1.400 jiwa tersebut, dalam praktiknya hanya beberapa ratus di antaranya saja yang sudah menjadi WNI.
Batas-batas negara modern kemudian melahirkan relasi bernama negara dan warga negara. Salah satu pendekatan untuk melihat negara dan relasinya dengan warga negara adalah konsep Komunitas Terbayang yang dicetuskan oleh Benedict Anderson, di mana negara bangsa dilihat sebagai komunitas yang dibangun secara sosial, dibayangkan oleh orang-orang yang menganggap diri mereka sebagai bagian dari suatu kelompok. Melalui konsep ini, dia mendefinisikan bangsa sebagai "komunitas politik yang dibayangkan.” Sebuah bangsa dianggap sebagai sebuah entitas yang "dibayangkan” karena anggota negara terkecil sekalipun tidak akan pernah mengenal sebagian besar anggotanya, bertemu dengan mereka, atau bahkan mendengar kabar tentang satu sama lain.
Anggota komunitas terbayang mungkin tidak akan pernah mengenal satu sama lain secara langsung; namun, mereka mungkin memiliki minat yang sama atau mengidentifikasi diri sebagai bagian dari negara yang sama. Para anggota komunitas terbayang memegang dalam pikiran mereka gambaran mental tentang afinitas mereka. Misalnya, rasa kebangsaan dengan anggota lain dari bangsanya ketika komunitas terbayang itu berpartisipasi dalam acara yang mengglorifikasi nasionalisme secara besar seperti Olimpiade atau Piala Dunia.
Kritik Anarkis atas Negara versus Kritik Usang terhadap Kritik Anarkis atas Negara
Segunung masalah yang melahirkan kekejian dan sederet kejahatan terhadap kemanusiaan yang mengerikan, maupun irasionalitas entitas bernama negara sebagaimana dikemukaan oleh Benedict Anderson, membuktikan kritik anarkisme terhadap keberadaan sebuah entitas bernama negara sebagai wujud dari hirarki absolut.
Akan tetapi, hal-hal tersebut tak juga mampu membuat sejumlah kalangan –yang sayangnya cukup besar– untuk mengakui kebenaran kritik kaum anarkis tentang pentingnya meniadakan negara, atau setidak-tidaknya mengambil posisi kritis terhadap keberadaan negara.
Bahkan, hal ini juga terjadi di sebagian besar kelompok gerakan sosial yang sudah cukup mampu untuk menerima gagasan pentingnya kritik atas negara, tetapi tidak dengan gagasan pentingnya kritik atas keberadaan entitas bernama negara.
Kelompok-kelompok yang denial terhadap kritik anarkis terhadap entitas negara, masih terjebak dalam gagasan usang bernama “pemerintahan yang baik” atau “good governance”, menganggap bahwa masalah-masalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan segala macam kengerian lain –yang selama ini menjadi fokus kerja mereka– termasuk pelanggaran-pelanggaran HAM, dapat dihapuskan apabila gerakan sosial yang reformis mampu mendorong adanya sistem pemerintahan yang baik, yang diisi dengan orang-orang ideologis, revolusioner, sehingga mampu menggeser para oligarki dengan segala kebesaran kuat dan kuasanya dari bangku pemerintahan dan posisi-posisi strategis dalam pengambilan keputusan dan melahirkan pemerintahan yang ideal, menjunjung tinggi HAM dan kemanusiaan, dan lainnya –seolah-olah hal tersebut memungkinkan untuk dilakukan.
Hal ini, dalam porsi tertentu, mirip dengan gagasan kaum Marxis tentang kediktatoran proletariat. Seolah-olah, kediktatoran kaum proletar, yang melalui revolusi dibayangkan mampu mengambil alih kekuasaan, akan berhasil mewujudkan gagasan masyarakat sosialis. Hal ini kita ketahui sebagai debat klasik antara Marx dan Bakunin yang sampai saat ini masih menjadi debat tak terselesaikan antara kaum Marxis dan kaum anarkis.
Kritik usang terhadap kritik kaum anarkis atas keberadaan negara dan gagasan anarkis untuk meniadakan negara, biasanya terbungkus dalam pertanyaan-pertanyaan sinis serupa “nanti siapa yang mengatur masyarakat?”, “kalau nggak ada negara dan masyarakat nggak ada yang pimpin, kacau dong?”, “kalau tidak ada negara dan perangkatnya seperti polisi dan tentara, nanti yang nangkap penjahat dan melindungi kita kalau diserang negara lain siapa?”, atau “memang bisa, hidup tanpa negara?”
Pertanyaan-pertanyaan semacam itu muncul sebagai wujud dari sangat sempitnya ruang imajinasi kita untuk mampu membayangkan bentuk-bentuk alternatif kehidupan bersama selain negara. Hal ini barangkali disebabkan karena sedari lahir hingga mati, sebagian besar dari kita hidup dalam kerangka negara, dimulai dari akta kelahiran hingga akta kematian yang semuanya harus dilegalisir negara, sehingga jika tidak ada dokumen-dokumen yang dilegalisir negara tersebut, maka seolah-olah kelahiran kita tidak sah, kita dianggap tidak pernah ada, dan kematian kita tidak berarti apa-apa.
Ini merupakan hasil dari proses internalisasi pikiran sepanjang ribuan tahun sejarah peradaban manusia yang selalu didominasi oleh keberadaan negara, dan prosesnya masih berlangsung hingga kini. Tidak ada jalan lain selain negara. Tidak ada cara kehidupan bersama lain selain bernegara. Sebagaimana kata “anarkis” masih diartikan dan disematkan dengan konotasi negatif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini adalah upaya mengkerdilkan imajinasi politik kita soal kemungkinan lain selain negara.
Faktanya, sejarah mencatat beberapa praktik hidup berkolektif dalam bentuk selain negara ada dan mungkin dilakukan. Ia pernah dipraktikkan di masa lalu dan ada yang masih dipraktikkan di masa sekarang.
Komune Paris pada 1871 adalah salah satu contoh yang bisa dilihat sebagai salah satu praktik. Sebagai upaya hidup bersama, Komune Paris lebih mirip kolektif yang dijalankan oleh para warga secara otonom, bebas dari pemerintahan negara Prancis, dan berhasil menaruh pondasi fundamental dalam perubahan cara kerja ekonomi yang tidak lagi kapitalistik tetapi mengembalikan kepemilikan dan kontrolnya pada para pekerja lewat model kerjasama pekerja. Sepanjang usia Komune Paris, 43 kerjasama pekerja berhasil terbentuk.
Selain Komune Paris, upaya lain yang bisa kita lihat juga adalah Revolusi Rojava, upaya pembangunan masyarakat berkelanjutan yang muncul di wilayah mayoritas Kurdi dalam konteks perang Suriah.
Sejak 2012, orang-orang yang terlibat di dalam eksperimen ini membingkai revolusi dan gagasan mereka tentang kewargaan demokratis radikal sebagai upaya peningkatan kesadaran melawan sistem negara.
Orang-orang dalam wilayah administratif Rojava sering disebut sebagai 'bangsa terbesar tanpa negara'. Penyematan konotasi negatif tentang kelompok yang terdiri dari sekitar 40 juta orang ini mencerminkan tatanan geopolitik dunia yang berpusat pada sistem negara, sebab Rojava tidak bekerja dengan cara negara bekerja: ia adalah sebuah administrasi otonom yang dibentuk untuk mengelola kehidupan bersama berdasarkan nilai-nilai demokrasi langsung.
Masyarakat yang hidup dan menghidupi revolusi ini terus membangun dan mengembangkan struktur politik yang relatif stabil. Lembaga hukum, seperti komite perdamaian, telah diperkenalkan. Badan-badan berbasis konsensus ini bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik dan sebagian besar telah menggantikan sistem pengadilan hirarkis yang umum dipraktikkan di negara-negara lain.
Rojava juga berhasil menciptakan dua kontrak sosial, semacam konstitusi yang diadopsi pada tahun 2014 dan 2016 sebagai hasil dari proses sosial kolaboratif di mana diskusi kolektif menentukan topik mana yang akan dimasukkan.
Komune Paris dan Revolusi Rojava. Kita bisa berdiskusi ataupun berdebat tentang bagaimana kedua upaya itu menyimpan kegagalan dan kekurangannya masing-masing. Toh, Komune Paris mampu dipatahkan dalam waktu tak lebih dari 70 hari, ia hanya mampu bertahan selama dua bulan sampai kota Paris dikepung oleh tentara Prancis.
Akan tetapi, barangkali waktu dua bulan bagi Komune Paris bukan waktu yang kepalang singkat untuk sebuah eksperimen yang merupakan antitesis total dari bagaimana negara dan kapitalisme bekerja. Pun demikian dengan konfederalisme demokratis yang menekankan pada otonomi wilayah-wilayah yang terlepas dari kekuasaan sentralistik negara berdasarkan politik partisipatif yang diwarnai nilai-nilai feminisme dan environmentalisme yang dieksperimenkan di Rojava.
Terbentang waktu lebih dari 100 tahun, keberadaan dua eksperimen anti negara ini merupakan perwujudan akan validnya kejengahan orang-orang pada entitas bernama negara dengan cara kerjanya yang disokong kapitalisme eksploitatif, yang sepaket dengan segala kekerasan, penindasan, penghisapan dan kejahatan terhadap kemanusiaan pada bukan hanya mereka yang merupakan warga negaranya, juga bagi mereka yang bukan warga negaranya.
Dan kejengahan itu tak lekang dimakan jaman.
Kedua eksperimen tersebut pada akhirnya berhasil membuktikan, bahwa kehidupan tanpa negara itu bukan hanya mampu diimajinasikan, tetapi juga memungkinkan.