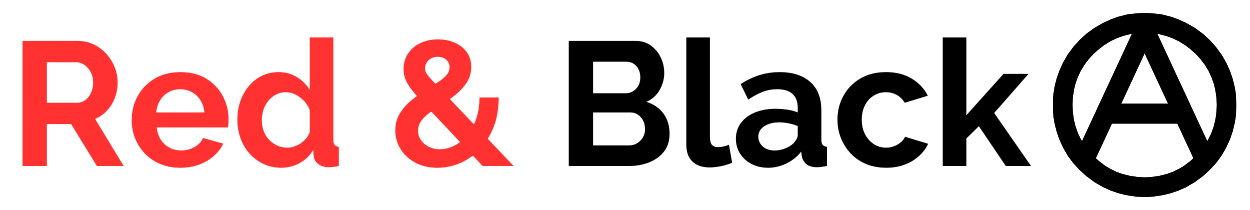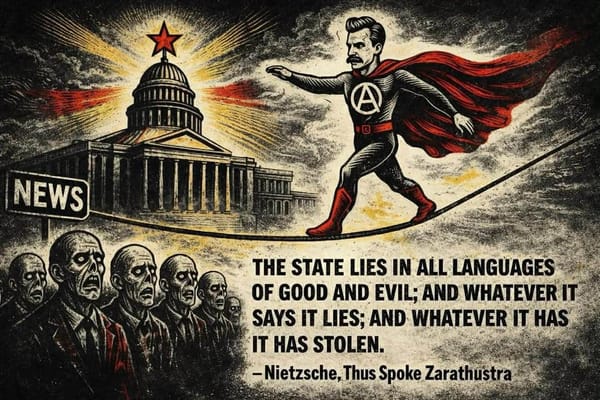Penolakan Revisi UU TNI: Anarkis di Persimpangan Jalan.

Meskipun mendapat penolakan besar-besaran sejak diwacanakan, revisi Undang-Undang TNI (RUU TNI) tetap disahkan 20 Maret 2025 lalu. Pasca pengesahan, penolakan dari masyarakat justru mengalami eskalasi dan melahirkan demonstrasi #TolakRUUTNI besar-besaran di seluruh penjuru Indonesia. Terhitung sejak 20 Maret 2025 hingga 28 Maret 2025, terdapat 69 aksi yang kesemuanya –tentu saja– mendapatkan represi gila-gilaan dari aparat negara.
Kekerasan terhadap mereka yang mengekspresikan penolakan terhadap RUU TNI terjadi di berbagai aspek, secara fisik juga digital. Tak terhitung jumlahnya pemukulan, penangkapan, penghukuman sewenang-wenang tanpa proses hukum, atau bahkan ancaman terhadap para petugas medis dan mobil ambulans yang membantu mengevakuasi korban kekerasan aparat negara. Tak hanya itu, persekusi digital juga kerap dialami oleh mereka yang menolak UU TNI yang baru direvisi (selanjutnya disebut UU TNI Baru) dalam ekspresi-ekspresi mereka di media sosial.
Kerja-kerja jurnalistik yang secara ideal konon menjadi prasyarat negara demokratis pun kemudian mendapatkan teror. Setidak-tidaknya tercatat ada dua kali kekerasan kepada Tempo, sebuah media yang selama ini dikenal kritis dan bekerja berlandaskan prinsip-prinsip jurnalisme yang baik. Pertama-tama, Tempo diteror dengan dikirimkan kepala babi, lalu 6 bangkai tikus yang kepalanya dipenggal. Keduanya dikirim dalam dua hari berbeda, 19 Maret 2025 dan dini hari 22 Maret 2025. Dugaan kuat, hal ini terkait dengan vokalnya Tempo menyuarakan penolakan terhadap pengesahan RUU TNI dalam produk-produk jurnalistiknya.
Dapat kita lihat bersama-sama, negara menggunakan segala macam upaya untuk tetap bersikeras mengesahkan RUU TNI.
Pertanyaan Sebenarnya, Apa Alasan di Balik Bersikerasnya Negara Mengesahkan RUU TNI?
Negara tentu saja tidak pernah terang-terangan mengungkapkan apa alasan di balik bersikerasnya ia mengesahkan RUU TNI. Tetapi pengesahan RUU TNI juga bukan berasal dari ruang hampa begitu saja. Ia merupakan bagian dari rentetan fakta yang telah terjadi sebelumnya.
Pertama, gestur otoritarianisme memang telah ditunjukkan sepanjang sejarah Indonesia berdiri sebagai republik, termasuk dan khususnya pada dua periode pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) pada tahun 2014 - 2024.
Dalam sepuluh tahun rezim Jokowi, represifitas kerap menyasar dan meminggirkan beberapa kelompok rentan—kelompok minoritas agama, ras, dan gender—yang keberadaannya tidak diterima oleh mayoritas masyarakat karena alasan perbedaan penafsiran agama, perbedaan ras dan etnis, dan sebagainya. Pemerintah sering kali berpihak pada kepentingan kelompok mayoritas dengan terus menerus melanggengkan stigma dan menjadikannya dalih melakukan diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap banyak kelompok rentan alih-alih melindungi semua orang tanpa memandang latar belakangnya. Hal ini dikenal dengan istilah mayoritarianisme, dan hal ini dilakukan untuk tetap mencari dukungan dari mayoritas untuk melanggengkan kestabilan kekuasaannya.
Kasus-kasus seperti pelarangan pendirian tempat ibadah, persekusi dan kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah, kelompok agama atau kepercayaan setempat, komunitas LGBTQA+, dan keberadaan hukuman mati dalam hukum positif di Indonesia, dan sebagainya, hanyalah beberapa contoh di antaranya.
Kemudian, menjelang pemilu 2024, Jokowi menggunakan kekuasaannya untuk membangun dinasti politik. Melalui saudara iparnya yang diberikan posisi sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, peraturan tentang batas minimal usia calon wakil presiden diubah menjadi lebih muda sehingga anaknya dapat mencalonkan diri, dan tentu saja, seperti yang sudah bisa kita tebak, ia terpilih menjadi wakil presiden.
Beberapa pakar hukum menyebut gelagat manipulasi hukum ini sebagai bentuk legalisme otokrasi.
Gestur otoritarianisme yang disokong militer pun semakin kuat tatkala rezim Jokowi terang-terangan menyatakan sikap politiknya yang tidak peduli pada pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh militer. Dalam sidang Universal Periodic Review pada 2022, sebuah mekanisme HAM di bawah PBB di mana setiap negara secara bergiliran ditinjau situasi HAM-nya, Indonesia menolak banyak rekomendasi perbaikan situasi HAM di dalam negeri, termasuk untuk melakukan proses hukum terhadap kekerasan yang dilakukan oleh aparat bersenjata –termasuk militer– di Papua.
Kedua, keberpihakan pada kepentingan pemilik modal besar, investasi, perusahaan multinasional, atau apapun sebutannya, juga sangat kentara dalam setidaknya sepuluh tahun masa pemerintahan Jokowi. Kapitalisme selalu menjadi alasan di balik serangkaian kekerasan sebagaimana ditulis dalam paragraf-paragraf sebelumnya, juga menjadi alasan di balik terjadinya serangkaian pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial, budaya atas banyak kelompok masyarakat di Indonesia.
Salah satu modus pembelaan terhadap hal-hal tersebut di atas adalah dengan menjadikan proyek-proyek bisnis para pemilik modal besar itu sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dalam praktiknya kerap merampas lahan warga maupun hak-hak masyarakat adat atas tanahnya. PSN, kemudian, dianggap bagian dari kebijakan pemerintah untuk melakukan pembangunan dan peningkatan ekonomi di dalam negeri. Pembelaan terhadap kepentingan-kepentingan pemilik modal besar itu dilakukan dengan dalih pembangunanisme.
Sepanjang tahun 2015 hingga 2023, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi setidak-tidaknya 73 konflik terkait PSN. Dari 161 PSN yang tercatat per September 2023, kesemuanya merampas tanah ulayat, yang menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) terjadi 301 kasus melibatkan perampasan 8,5 hektar tanah masyarakat adat hanya dalam kurun waktu 2018 hingga 2022.
Atas nama pembangunan itu pula, rezim Jokowi membungkam siapa saja yang melawan kebijakan pembangunanisme-nya. Tuduhan “melawan kepentingan nasional” dijadikan justifikasi atas sederet represi dan kekerasan yang dilakukan di berbagai wilayah administratif Indonesia.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat tingginya kriminalisasi terhadap pembela HAM dan lingkungan dalam PSN. Hingga 2023, dari 35 proyek PSN yang diadvokasi LBH - LBH yang dinaungi YLBHI, sedikitnya 85 orang dikriminalisasi. Tercatat sebanyak 212 letusan konflik agraria yang mengakibatkan 497 kasus kriminalisasi pejuang hak tanah (land rights defenders). Sedikitnya, 268 pembela HAM, isu lingkungan, dan masyarakat adat diserang.
Legalisme otokrasi atau manipulasi hukum juga secara konsisten dilakukan secara brutal dalam nama membela kepentingan negara dan para pemilik modal besar itu, yang kemudian dapat kita sebut sebagai para oligarki. Hukum-hukum drakonian serupa UU ITE maupun Revisi KUHP dibuat untuk menjustifikasi pembungkaman kritik atas kebijakan-kebijakan pemerintah pro kapitalis tersebut.
Serangkaian hukum juga kemudian dibuat untuk memastikan para oligarki ini dapat semakin sewenang-wenang melakukan penindasan terhadap kelompok masyarakat adat, melakukan perampasan lahan, dan menjamin pemilik modal semakin dapat melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam dan pekerja, dan dilindungi oleh hukum positif.
Yang terakhir disebut mewujud dalam dibuatnya Omnibus Law Cipta Kerja yang dibuat dengan sembunyi-sembunyi di masa paceklik Covid-19 dan menjadikan pandemi itu sebagai alasan memukul gerakan penolakan besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia terhadap undang-undang tersebut.
Keberpihakan gila-gilaan pada kepentingan para oligarki maupun serangkaian pembuatan hukum yang melanggar hukum itu sendiri di kemudian hari menjadi bola salju kemarahan publik yang mengkristal menjadi dua gelombang aksi besar berikutnya, yakni aksi #PeringatanDarurat pada Agustus 2024 dan aksi #IndonesiaGelap pada Februari 2025. Khusus soal ini, akan dituang dalam tulisan lain.
Ketiga, latar belakang Prabowo sebagai mantan perwira tinggi Angkatan Darat. Prabowo Subianto adalah mantan jenderal Angkatan Darat yang menghabiskan lebih dari separuh hidupnya menjadi bagian dari Angkatan Darat di era Soeharto, yang selain sebagai sebuah institusi, Angkatan Darat memang terlibat dalam banyak pelanggaran HAM maupun pelanggaran HAM berat, Prabowo sebagai individu pun secara spesifik terlibat dan seharusnya bertanggung-jawab atas beberapa pelanggaran HAM berat tersebut.
Ia terlibat dalam Operasi Seroja yang dilakukan Angkatan Darat selama pendudukan Indonesia atas Timor-Timur (kini Timor-Leste) sepanjang tahun 1975 - 1998. Operasi Seroja secara keseluruhan diperkirakan memakan puluhan ribu korban jiwa. Secara spesifik, Prabowo (diduga kuat) terlibat dalam pembantaian Santa Cruz, yang terjadi di Pemakaman Santa Cruz, di mana ratusan orang yang sedang menghadiri pemakaman seorang pejuang kemerdekaan Timor-Leste diberondong dengan timah panas senjata tentara. Korbannya sekurang-kurangnya 271 orang. Ada yang mengatakan lebih dari 300. Atau kita juga bisa menyebut Pembantaian Kraras, yang juga terjadi dalam Operasi Seroja, yang juga memakan ratusan korban jiwa.
Di luar Operasi Seroja, Prabowo juga (lagi-lagi, diduga kuat) terlibat dalam penculikan beberapa aktivis pro-demokrasi. Tim Mawar adalah tim khusus di bawah Kopassus yang sengaja dibentuk untuk membungkam kritik dari para aktivis pro demokrasi sepanjang tahun 1996 hingga 1998. Pada waktu itu, Prabowo adalah Komandan Jenderal Kopassus. Penculikan yang dilakukan Tim Mawar membunuh dan menghilangkan secara paksa belasan aktivis pro-demokrasi. Beberapa berhasil kembali, tapi sampai sekarang setidaknya ada 13 orang yang masih belum diketahui keberadaannya.
Dilema Anarkis dalam Penolakan RUU TNI
Dalam aksi-aksi diskusi, demonstrasi, ataupun gerakan di media sosia terkait penolakan #TolakRUUTNI, terlihat banyak anarkis yang terlibat. Atau, setidak-tidaknya, mereka yang berpenampilan khas anarkis, dengan baju atau bendera A bulat maupun simbol-simbol anarkis lainnya, serta dilengkapi dengan slogan-slogan khas anarkis dan mural-mural yang juga bergambar simbol-simbol anarkis.
Sebagai anarkis, tentu kita sudah mafhum dengan perdebatan klasik acap kali kita melihat kasus-kasus serupa di mana ada para anarkis yang terlibat dalam demonstrasi, diskusi, atau bentuk ekspresi lainnya yang ikut menolak pembentukan hukum dalam sebuah negara. Spesifik dalam hal ini, RUU TNI atau UU TNI Baru.
UU TNI Baru secara hukum menggantikan UU TNI yang sebelumnya ada (selanjutnya disebut UU TNI Lama). Bila kita lihat secara hitam putih, maka dapat dianggap, penolakan terhadap UU TNI Baru adalah dukungan untuk tetap mempertahankan UU TNI Lama.
Dengan terlibatnya para anarkis dalam penolakan UU TNI Baru ini, mungkin sebagian dari kita tergelitik dengan argumen-argumen di dalam kepala kita sendiri, semacam “mengapa para anarkis ikut-ikutan menolak undang-undang baru? Apakah ini artinya mereka mendukung undang-undang lama, yang mana kita ketahui undang-undang adalah produk negara? Bukankah anarkis seharusnya tidak bergerak dalam koridor negara? Apakah ini pertanda anarkis mengakui negara?”
Sebelum kita sampai pada diskursus itu, mungkin penting pertama-tama kita memahami beberapa alasan kunci mengapa UU TNI Baru ini perlu ditolak.
Pertama, UU TNI Baru membuka jalan yang lebih lebar bagi anggota TNI untuk masuk ke ranah sipil, termasuk pada soal lapangan pekerjaan. UU TNI Baru menyatakan anggota TNI dapat menempati posisi-posisi sipil di 16 kementerian/lembaga negara. Sementara, atas alasan efisiensi anggaran negara, pemecatan aparat sipil negara (ASN) sudah terjadi di mana-mana, pengangkatan calon aparat sipil negara (CASN) ditunda dan menyebabkan tingkat pengangguran menjadi tinggi. Di tengah kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan, anggota TNI malah dibukakan jalan yang selebar-lebarnya untuk memiliki dua pekerjaan.
Jumlah 16 kementerian/lembaga negara yang dibuka untuk anggota TNI mungkin terlihat kecil. Tapi faktanya, meskipun UU TNI Lama hanya mengizinkan anggota TNI bekerja di 10 kementerian/lembaga negara saja, tercatat ribuan anggota TNI bekerja di ribuan posisi sipil.
Imparsial mencatat, pada 2023, terdapat 2.569 prajurit aktif TNI yang menempati jabatan sipil. Sementara, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) mencatat 86 MoU antara TNI dengan lembaga sipil. Tandanya, ini bukan hanya soal jumlah, tetapi tentang upaya melegitimasi mereka semakin merampas hak masyarakat atas lapangan kerja yang layak. Ini sangat berdampak pada kehidupan kelas pekerja di Indonesia yang merupakan fokus isu kelompok anarko-sindikalisme.
Kedua, fakta bahwa UU TNI Baru dibuat dengan semangat menarik kembali militer ke dalam ruang sosial-politik dan ekonomi-bisnis sipil, menyimpan begitu banyak kebahayaan. TNI hidup dalam hukum militer yang dalam prakteknya selalu dijalankan secara tertutup, dan sarat impunitas. Hal ini mengancam keberadaan hak-hak sipil masyarakat karena TNI dapat bertindak secara sewenang-wenang.
Selama ini, diskursus soal anarkisme secara umum, maupun anarko-sindikalisme secara khusus, hidup dalam ruang-ruang sipil.
Pasca Reformasi 1998, militer ditarik dari ruang sipil. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dipecah menjadi TNI dan Polri, di mana TNI ditugaskan mengurus urusan pertahanan, dan Polri ditugaskan mengurus urusan keamanan dalam negeri.
Ditariknya kembali militer ke ruang sipil akan membahayakan keberadaan diskursus soal anarkisme, juga para anarkis itu sendiri.
Terlebih, beberapa tahun terakhir, tepatnya sejak 2018, keberadaan anarkisme dan/atau kelompok anarkis telah dijadikan kambing hitam baru oleh aparat negara, khususnya militer, sebagai upaya mereka melegitimasi bahwa ada ancaman keamanan dan pertahanan bagi keberadaan negara. Hal ini mulai dilakukan sebab hantu komunisme tak lagi terlalu mampu dijadikan kambing hitam.
Sebagai catatan, hantu komunisme selalu dijadikan kambing hitam selama kepemimpinan Soeharto pada tahun 1965 - 1998, yang juga mantan perwira tinggi Angkatan Darat. Dengan tuduhan kudeta bersenjata yang disematkan pada Partai Komunis Indonesia (PKI), militer khususnya Angkatan Darat melakukan “bersih lingkungan” dengan membunuh orang-orang yang dianggap anggota atau sekadar terafiliasi dengan PKI atau underbouw-underbouwnya. Sepanjang 1965 - 1966, berdasarkan temuan beberapa sejarawan dan Indonesianis seperti salah satunya Benedict Anderson, tercatat 500.000 - 3.000.000 orang terbunuh, belum termasuk mereka yang dipenjara tanpa pengadilan, atau yang menjadi eksil dan tak bisa kembali.
Dengan tidak adanya perang atau ancaman pertahanan negara dari luar, militer butuh kambing hitam untuk tetap merasa relevan, juga tentunya agar tetap dapat mengakses APBN. Maka dari itu, belajar dari pengalamannya menjadi relevan selama pemerintahan militeristik Soeharto, dalam pembuatan UU TNI Lama, tugas militer diklasifikasikan menjadi dua, yakni Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Beberapa tugas yang tercakup dalam OMSP di antaranya adalah mengatasi terorisme separatisme bersenjata, dan pemberontakan bersenjata.
Ketiga, UU TNI Baru menambah tugas OMSP militer. Secara spesifik, UU TNI Baru mengizinkan militer untuk melakukan operasi siber dengan dalih membantu dalam upaya menanggulangi ancaman pertahanan siber, terutama yang menyerang sistem pertahanan. Perlu dicatat, selama ini, banyak individu atau kelompok anarkis yang menggerilyakan ide dan gagasannya lewat ruang-ruang siber.
Dengan fakta bahwa sejak beberapa tahun terakhir anarkisme dan/atau anarkis mulai diidentifikasi sebagai ancaman, diizinkannya militer memata-matai masyarakat sipil dan masuk ke ruang-ruang sipil, tentu –lagi-lagi– akan berdampak pada keberadaan diskursus-diskursus soal anarkisme, maupun para anarkis itu sendiri. Terlebih, dengan membaca rekam jejak Prabowo dengan latar belakang militer yang kuat dan keterlibatannya dalam membungkam suara-suara kritis atau yang dianggap mengganggu kestabilan negara.
Anarkis di Persimpangan Jalan
Argumen-argumen serupa “anarkis tidak perlu ikut-ikutan menolak RUU TNI karena undang-undang apapun adalah produk negara” sebagaimana telah ditulis di beberapa paragraf sebelum ini, tentu ada dan valid.
Di saat bersamaan, kemarahan dan kekhawatiran yang muncul dengan disahkannya RUU TNI juga ada dan tak kalah validnya. Bahkan, barangkali, ia hadir disertai urgensi yang tinggi, karena mengancam keberlangsungan diskursus anarkisme maupun keberlangsungan hidup para anarkis itu sendiri.
Keberadaan dua hal di atas barangkali membuat anarkis berada di persimpangan jalan: antara memilih jalan yang satu, dengan pertimbangan tertentu, atau memilih jalan yang satunya lagi, dengan pertimbangan tertentu yang barangkali sama-sama benar.
Beruntungnya, anarkisme bukanlah ideologi yang mengharuskan keseragaman seperti ideologi-ideologi lain. Kita bisa, dan sah-sah saja, untuk berbeda pendapat dan mengambil jalan ataupun rute yang tak sama, yang tak harus selalu lurus dan barangkali sedikit memutar. Tak ada jalan yang lebih baik untuk menang, tak ada jalan yang lebih baik untuk kalah.
Tapi sebelum berbicara soal jalan atau metode yang bisa jadi berbeda, para anarkis tentu bersepakat mutlak pada satu hal: bahwa betul anarkisme menentang segala bentuk hirarki, tapi yang pertama-tama ia tentang adalah segala bentuk penindasan. Dan penindasan adalah selalu kekuasaan. Segala bentuk; tak peduli apakah ia berbentuk sistem atau tidak
Pada akhirnya, alasan anarkisme ada adalah untuk melawan ancaman kekuasaan. Kekuasaan harus disetarakan, agar tak ada yang menguasai ataupun dikuasai –setidak-tidaknya oleh ketakutan. Upaya saya pribadi, atau mungkin juga para anarkis lain yang ikut menolak RUU TNI, bukanlah bentuk pengakuan terhadap negara atau kekuasaan, melainkan upaya untuk menyetarakan kekuasaan itu sendiri.